Oleh: Sofyano Zakaria
Menarik untuk dicermati bahwa setiap kali muncul “persoalan”, bahkan yang skalanya kecil sekalipun, yang menyangkut Pertamina , maka seolah seolah “sebagian pihak” langsung berloma menjadi “hakim” menghakimi Pertamina.
Tidak jarang, kasus yang sebenarnya bersifat teknis sekalipun, dimaknai secara politis, dibesar besarkan bahkan di dramatisasi sedemikian rupa seolah Pertamina adalah sumber dari segala masalah di negeri ini.
Bahkan yang lebih “menyedihkan” , sering kali persoalan teknis yang sebenarnya bisa diselesaikan secara internal, berubah menjadi isu politik yang mengundang perdebatan panjang.
Ada yang memanfaatkan momentum itu untuk menyerang pemerintah, ada yang mencari panggung populis, dan ada pula yang hanya ikut arus karena “menyerang” mengkritik BUMN Besar dianggap sebagai tren.
Pertamina bukan perusahaan biasa. Ia adalah simbol energi nasional, tulang punggung distribusi bahan bakar dan energi di seluruh pelosok negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, tidak ada daerah yang tidak bergantung pada peran Pertamina.
Namun karena peran strategisnya itulah, Pertamina seolah tidak punya ruang untuk salah. Setiap insiden ,entah tumpahan minyak, antrean di SPBU, keterlambatan distribusi elpiji, bahkan perbedaan harga beberapa rupiah langsung menjadi berita besar. Tidak jarang pula dijadikan bahan politisasi oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan popularitas isu energi untuk kepentingan tertentu.
Padahal kalau mau jujur, sebagian besar masalah yang menimpa Pertamina bersifat operasional dan teknis, bukan kebijakan atau korporasi. Kilang minyak terbakar misalnya, bisa terjadi di mana pun di dunia. Distribusi BBM terganggu karena cuaca ekstrem atau kendala logistik pun merupakan hal yang manusiawi. Namun di Indonesia, ketika hal itu menimpa Pertamina, maka framing-nya seolah-olah itu “bukti kegagalan sistemik”.
Sebaliknya, ketika Pertamina bekerja keras dan berhasil menjalankan tugas besar yang bahkan di negara lain ditangani oleh banyak perusahaan sekaligus, apresiasi nyaris tidak terdengar.
Di saat Pandemi COVID 19 dimana konsumsi energi dunia anjlok, harga minyak jatuh, dan logistik terganggu Pertamina tetap menjaga ketahanan energi nasional bahkan mempelopori sumbangan nyata buat masyarakat .
Namun publik seolah lupa bahwa Indonesia tidak pernah mengalami kelangkaan BBM yang signifikan pada masa itu.
Begitu juga ketika harga minyak dunia naik tajam, Pertamina menahan harga BBM bersubsidi agar rakyat tidak terbebani. Padahal, konsekuensinya jelas: keuangan perusahaan harus menanggung selisih harga yang luar biasa besar. Tapi karena langkah itu dianggap “kewajiban BUMN”, maka tidak ada pujian, hanya komentar datar: “Ya memang tugasnya begitu.”
Sikap seperti ini mencerminkan bagaimana sebagian masyarakat tidak lagi mampu membedakan antara kewajiban dan pengabdian. Padahal, menjalankan kewajiban dengan konsistensi dan integritas juga merupakan bentuk pengabdian yang layak dihargai.
Kita seperti lupa bahwa BUMN juga entitas bisnis. Pertamina memang milik negara, tapi bukan berarti semua bebannya harus dipikul tanpa apresiasi.
Tidak ada yang menolak kritik terhadap Pertamina. Bahkan justru, sebagai pengamat kebijakan energi, saya meyakini kritik adalah bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas. Namun yang jadi persoalan adalah ketika kritik itu tidak lagi bersifat konstruktif, melainkan destruktif , tendensius dan lebih terdengar sebagai pelampiasan emosi terhadap “BUMN”
Kita bisa lihat pola yang berulang: setiap kali ada isu di Pertamina, banyak pihak bereaksi berlebihan sebelum fakta terungkap. Padahal, dalam konteks korporasi besar dengan ribuan proyek dan kegiatan, tentu saja potensi masalah selalu ada. Tapi di perusahaan swasta, kejadian serupa jarang menjadi headline.
Mengapa? Karena nama Pertamina terkesan jauh lebih “seksi” untuk diberitakan.
Ada semacam euforia publik terhadap setiap hal negatif yang menimpa BUMN besar, apalagi yang berhubungan dengan energi. Seolah-olah menemukan kesalahan Pertamina adalah sebuah prestasi tersendiri.
Padahal, Pertamina bukan malaikat, tapi juga bukan kambing hitam.
Jika ada kekeliruan, tentu harus dibenahi. Tapi kalau ada keberhasilan, jangan pura-pura tidak tahu.
Ketika Pertamina menuntaskan proyek besar seperti pembangunan kilang, peningkatan kapasitas terminal BBM, atau mengembangkan energi baru dan terbarukan, “komentarnya” tidak seramai ketika ada pipa bocor atau SPBU kehabisan stok. Padahal, kontribusi semacam itu memiliki dampak jangka panjang terhadap kemandirian energi nasional.
Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa isu energi selalu memiliki dimensi politik.
BBM, elpiji, dan listrik menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Karena itu, siapa pun yang bisa memanfaatkan isu ini, otomatis bisa menarik perhatian publik.
Maka ketika Pertamina tersandung kasus — sekecil apa pun — narasi yang muncul bukan lagi soal teknis, tapi langsung diarahkan ke ranah politik. Ada yang menuding pemerintah tidak becus, ada yang menuduh manajemen Pertamina tidak profesional, bahkan ada yang menuding ini semua permainan oligarki.
Padahal, banyak tudingan itu muncul tanpa dasar data, hanya bersumber dari opini di media sosial.
Sementara pihak yang benar-benar paham industri migas tahu betul: tantangan di sektor ini sangat kompleks dan berisiko tinggi.
Setiap kebijakan di dunia energi tidak bisa dipisahkan dari dinamika global. Harga minyak, distribusi, geopolitik, hingga kebijakan transisi energi semua saling terkait. Maka ketika ada persoalan di Pertamina, mestinya publik memahami konteks globalnya, bukan langsung melemparkan vonis.
Ada yang salah kaprah di masyarakat: memberi apresiasi pada Pertamina sering dianggap sebagai bentuk pembelaan atau pencitraan.
Padahal tidak.
Apresiasi adalah pengakuan terhadap kerja keras dan kontribusi nyata.
Tidak ada salahnya jika publik memberi penghargaan moral pada BUMN yang terus berupaya memenuhi kebutuhan energi nasional, bahkan di tengah situasi sulit.
Kita sering memuji perusahaan asing ketika mereka berhasil, tapi mengapa begitu pelit memuji perusahaan milik bangsa?
Apakah karena Pertamina sudah dianggap “pasti mampu”?
Jika bangsa ini ingin memiliki perusahaan energi yang kuat dan berdaya saing global, maka dukungan publik menjadi bagian penting. Dukungan bukan berarti menutup mata pada kesalahan, tapi memberi ruang bagi perbaikan tanpa caci maki.

Di balik logo Pertamina, ada ratusan ribu pekerja — anak-anak bangsa — yang bekerja siang malam memastikan energi tetap mengalir.
Mereka yang bertugas di laut, di sungai , di kilang, di gunung, hingga pelosok pulau terpencil yang kadang bekerja jauh dari keluarga, dalam risiko tinggi, untuk memastikan bahwa masyarakat bisa menyalakan kompor, menyalakan motor, dan menyalakan lampu setiap hari. Apakah mereka tidak layak dihargai?
Kritik boleh, tapi jangan sampai menghancurkan semangat mereka.
Karena kalau semangat itu hilang, maka yang rugi bukan Pertamina, tapi bangsa ini sendiri.
Pertamina bukanlah perusahaan tanpa dosa. Tapi juga bukan perusahaan tanpa jasa.
Selama puluhan tahun, Pertamina telah menjadi bagian dari denyut nadi ekonomi Indonesia. Ia mengalirkan energi ke rumah tangga, ke industri, ke daerah perbatasan — sesuatu yang sering dianggap “biasa” padahal luar biasa.
Kita boleh menuntut Pertamina agar lebih baik, lebih transparan, lebih efisien. Tapi dalam waktu yang sama, kita juga wajib berlaku adil dalam menilai.
Karena membangun bangsa bukan hanya dengan kritik, tapi juga dengan apresiasi.
Dan mungkin sudah saatnya kita belajar menempatkan Pertamina bukan sebagai kambing hitam setiap kali ada masalah, tapi sebagai mitra kebanggaan nasional yang harus terus kita dukung, awasi, dan banggakan.
Jika kita ingin bangsa ini mandiri dalam energi, maka langkah pertama adalah sederhana: Mulailah menghargainya.[•]
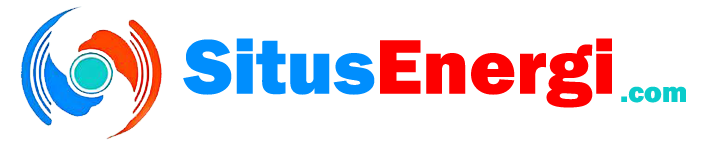







Leave a comment