Catatan Reflektif Akademis
Dari Artificial Intelligence ke Artificial Sustainability.
Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence, AI) telah menjadi ikon abad ke-21, lambang peradaban digital yang menggeser batas antara kemampuan manusia dan mesin. Namun, di balik gemerlapnya “kecerdasan buatan” tersimpan paradoks besar: semakin cerdas sistem AI, semakin besar pula energi yang ia konsumsi. Paradoks inilah yang melahirkan istilah baru dalam wacana teknologi dan keberlanjutan: Artificial Sustainability — upaya menyeimbangkan kemajuan AI dengan kelestarian ekologi dan etika energi.
AI hari ini bukan lagi sekadar algoritma di laboratorium, melainkan infrastruktur global yang haus daya. Pelatihan model GPT, LLaMA, atau Gemini membutuhkan energi listrik setara konsumsi kota kecil. Setiap jawaban yang dihasilkan mesin membawa jejak karbon yang tak kasat mata. Maka, muncul pertanyaan filosofis sekaligus moral: apakah kecerdasan digital yang menguras bumi masih dapat disebut “cerdas”?
Jejak Energi dan Dilema Moral Teknologi.
Menurut laporan International Energy Agency (IEA, 2023), konsumsi listrik pusat data dan jaringan AI global telah melewati 1% dari total listrik dunia, dan angka ini diperkirakan berlipat dua pada 2030. Di sisi lain, sebagian besar server masih disuplai dari listrik berbasis batubara, terutama di Asia. Ironinya, teknologi yang diciptakan untuk memecahkan krisis energi kini berpotensi memperburuknya.
Di sinilah etika teknologi diuji. Aristoteles dalam Ethica Nicomachea menegaskan bahwa kebajikan terletak pada moderasi, bukan ekstremitas . AI yang tak dikendalikan oleh prinsip keberlanjutan berisiko menjadi “otak buatan tanpa hati ekologis”. Dalam konteks ini, Artificial Sustainability bukanlah pilihan opsional, melainkan keharusan moral dan eksistensial —sebuah bentuk virtue ethics dalam era digital.
Green AI: Dari Efisiensi ke Ekologi.
Gerakan Green AI muncul sebagai antitesis terhadap Red AI—istilah untuk model besar yang haus sumber daya. Green AI mendorong riset untuk efisiensi energi komputasi, pemanfaatan chip hemat daya, dan algoritma ramah karbon.
Studi oleh Patterson et al. (2021) menunjukkan bahwa optimasi algoritma dan penggunaan energi terbarukan dapat menurunkan jejak karbon AI hingga 90%. Artinya, keberlanjutan bukan utopia teknis, melainkan hasil dari desain etis dan kebijakan yang visioner.
Namun, keberlanjutan buatan (artificial sustainability) tak hanya soal mengganti batubara dengan surya atau angin. Ia menuntut perubahan paradigma: dari mengejar bigger models menuju better models — dari kuantitas parameter menuju kualitas solusi.
Dalam bahasa Heidegger, manusia harus “ mengungkap kembali makna teknologi ” bukan sebagai Gestell (alat penakluk alam), tetapi sebagai poiesis, karya penciptaan yang menyatu dengan harmoni kosmos .
Indonesia di Persimpangan Digital-Energi.
Indonesia memiliki peluang sekaligus tantangan besar. Dengan potensi energi terbarukan mencapai lebih dari 400 GW, negeri ini dapat menjadi pusat data hijau Asia Tenggara, jika mampu mensinergikan kebijakan AI nasional dengan transisi energi bersih.
Pusat data di Batam, Cikarang, dan Cibitung bisa menjadi Green Digital Hub bila ditopang oleh listrik dari floating solar farm Cirata atau geothermal Dieng.
Namun, realitas di lapangan masih kontras: sebagian besar server nasional masih tergantung pada energi fosil. Di sinilah Artificial Sustainability perlu diartikulasikan sebagai strategi lintas sektor — menggabungkan kebijakan energi, inovasi digital, dan regulasi lingkungan.
Kementerian ESDM bersama BRIN dan Kominfo dapat menginisiasi Green AI Consortium—sebuah kolaborasi akademik, industri, dan pemerintah untuk mengembangkan algoritma efisien, pusat data netral karbon, serta indikator keberlanjutan AI nasional.

Dari Etika ke Kebijakan: Menuju Kecerdasan yang Berkelanjutan
Keberlanjutan buatan menuntut integrasi antara ethics, economics, and engineering.
Etika menuntun arah, ekonomi menentukan insentif, dan rekayasa memastikan solusi.
Dalam kerangka policy design, Green AI harus dipandang bukan sekadar proyek teknologi, melainkan infrastruktur moral bagi masa depan digital manusia.
Sebagaimana Aristoteles menempatkan phronesis (kebijaksanaan praktis) di atas sekadar pengetahuan teknis, demikian pula AI harus diarahkan oleh wisdom, bukan sekadar intelligence.
Green AI bukanlah tentang meniru kecerdasan manusia, tetapi tentang memantulkan kebijaksanaan alam—bagaimana sistem yang efisien bisa hidup berdampingan dengan ekosistemnya.
AI yang Bijak, Bukan Sekadar Cerdas
Jika awal abad ke-21 dikenal sebagai era Artificial Intelligence, maka akhir abad ke-21 harus menjadi era Artificial Sustainability.
AI tidak boleh menjadi monster digital yang memakan daya bumi, melainkan guru baru bagi manusia untuk belajar menyeimbangkan logika dan etika, energi dan empati, kemajuan dan keberlanjutan.
Sebab sebagaimana bumi mengajarkan keterbatasan, teknologi pun harus belajar rendah hati. Dan mungkin, dalam keseimbangan itulah kita menemukan hakikat “kecerdasan sejati” — bukan hanya yang berpikir, tetapi juga yang menjaga.
|A||N||S|
Dosen-GBUI
Buitenzorg,
22Nopember2025
Verba volant, scripta manent
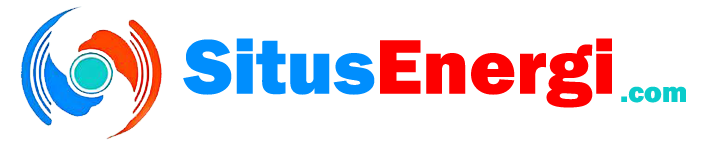







Leave a comment