Jakarta, situsenergi.com
Kita hidup di zaman di mana kampus lebih sibuk memoles citra daripada memperbaiki nasib lulusannya. Setiap brosur universitas kini seperti katalog kecantikan akademik: “World Class University”, “Top 200 QS Ranking”, “Sustainable Campus”, “AI-Driven Learning Environment”. Lengkap dengan logo ISO, drone shot gedung baru, dan testimoni alumni yang ( kalau jujur ) sebenarnya kerja di bidang yang tak ada hubungannya dengan jurusannya.
Sementara itu, para sarjana kita—produk unggulan dari sistem pendidikan nasional—berbaris rapi di antrean job fair, menyerahkan CV sambil berharap lowongan magang dibayar bukan sekadar ganti nama dari “kerja tanpa kontrak.”
Ranking Dunia: Ilusi Global, Ironi Lokal
Universitas besar seperti UI, ITB, dan UGM kini berlomba-lomba naik peringkat dunia. QS ( Quacquarelli Symonds ) , THE ( Times Higher Education ) , dan Times Higher Anything jadi kiblat baru, seolah masa depan bangsa tergantung pada ranking yang dibuat oleh lembaga di London yang bahkan tak tahu letak Sleman itu di Jawa bagian mana.
Akibatnya, riset diarahkan bukan untuk menjawab masalah negeri—seperti stunting, ketimpangan energi, atau birokrasi anggaran riset yang absurd—tapi untuk memenuhi indikator internasionalisasi.
Kampus pun berubah jadi pabrik akreditasi: menargetkan publikasi Scopus, mahasiswa asing, dan dosen tamu dari luar negeri. Padahal, mahasiswa dalam negeri masih berjuang mencari tempat magang yang seharusnya sesuai dengan bidang nya dan tidak sekedar bikin kopi ditempat magang.
Jadi pertanyaannya: untuk siapa kampus ini sebenarnya dibangun? Untuk bangsa, atau untuk ranking sheet?
Sarjana Menganggur: Antara Excel, Ekspektasi, dan Eksistensi
Ironinya, makin tinggi ranking kampus, makin banyak pula sarjana yang menganggur. UI bangga naik peringkat, tapi alumninya sibuk bikin side hustle jualan kopi literan. ITB mempromosikan Center of Excellence, tapi lulusan tekniknya bekerja di startup yang menjual template PowerPoint. UGM menelurkan ribuan sarjana sosial, tapi masyarakatnya tetap sosial hanya di media sosial.
Mungkin sudah saatnya kampus mengakui satu fakta pahit: pasar kerja tidak membaca jurnal Scopus.
Yang dibutuhkan bukan hanya nilai IPK, tapi kemampuan hidup — adaptasi, komunikasi, kolaborasi, dan sedikit keberanian untuk tidak baper.
Magang Dibayar, Revolusi atau Rekrutmen Halus?
Kebijakan “magang dibayar” disebut sebagai solusi. Konon agar mahasiswa mendapat pengalaman dunia nyata. Tapi di lapangan, “dibayar” sering berarti Rp750.000 per bulan, cukup untuk ongkos Transjakarta dan dua gelas kopi non-diskon.
Kampus bangga karena partnership with industry meningkat, tapi mahasiswa tahu: mereka sedang dilatih menjadi buruh digital yang efisien dan patuh. Work readiness, katanya. Padahal, lebih tepat disebut budget readiness — siap bekerja dengan gaji minimum dan ekspektasi maksimum.
Solusi Sederhana untuk Paradoks Kompleks
Kampus kita tidak perlu sibuk mengejar pengakuan dunia, kalau dunia kerja dalam negeri saja belum mengakui potensi lulusannya.
Sudah saatnya ranking kampus diukur dari seberapa banyak alumninya yang bisa hidup layak, bukan dari jumlah jurnal Scopus atau mahasiswa asing yang eksotik.
PTN seperti UI, ITB, dan UGM semestinya membuat “Ranking Nasional Mahasiswa Dalam Negeri” — bukan untuk menyaingi QS atau THE, tapi untuk menegakkan martabat bangsa sendiri.
Indikatornya bukan international reputation, tapi:
- Jumlah riset yang berdampak langsung pada masyarakat Indonesia.
- Persentase alumni yang menciptakan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan.
- Kepuasan rakyat, bukan sekadar citation index.
- Jumlah Invensi dan Patent Universitas yang di lisensi ( tidak hanya terdaftar di kantor DJKI ) oleh IKM dan Industri Nasional.
Kalau perlu, setiap universitas wajib menerbitkan Laporan Dampak Sosial: berapa banyak desa terbantu oleh riset mahasiswa, berapa UMKM yang naik kelas berkat kerja sama kampus, dan berapa dosen yang berhasil menulis jurnal tanpa kehilangan hati nurani.
Sarkasme yang Serius
Lucunya, kita sudah terlalu lama bangga disebut “world class”, padahal dunia pun belum tentu tahu kita eksis.
Mungkin sudah waktunya berhenti mengejar recognition abroad, dan mulai membangun relevance at home.
Karena sejatinya, universitas bukanlah menara gading untuk selfie intelektual, tapi dapur kebangsaan: tempat mencampur ilmu dan empati, teori dan kenyataan, idealisme dan akal sehat.

Kalau Plato masih hidup, ia mungkin akan menulis ulang The Republic versi Indonesia:
Negara yang sibuk memoles ranking kampusnya, tapi lupa mengangkat harkat mahasiswanya—adalah negara yang sedang magang di peradaban.
|A||N||S|
Buitenzorg,
26Oktober2025
Verba volant, scripta manent
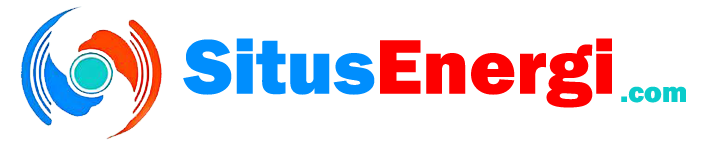







Leave a comment